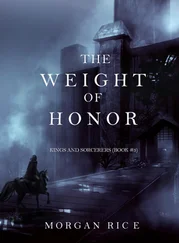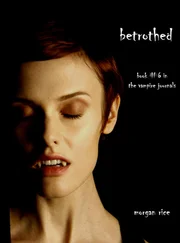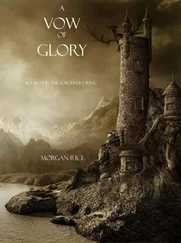Caitlin sangat tidak ingin pulang. Ia tidak ingin berurusan dengan Ibunya, khususnya hari ini, tidak ingin berurusan dengan tempat baru, dengan tidak berkemas. Jika itu tidak karena Sam beradd di sana, ia mungkin telah berpaling dan pergi. Ke mana ia akan pergi, ia tidak ada gagasan - tapi paling tidak ia akan berjalan.
Ia mengambil napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan serta meletakkan tangannya di pegangan pintu. Entah kenapa pegangan pintu itu hangat, atau tangannya yang sedingin es.
Caitlin memasuki apartemen yang terlalu terang itu. Ia bisa mencium bau makanan di atas kompor - atau mungkin, dalam microwave. Sam. Ia selalu pulang lebih cepat dan membuat makanan untuk dirinya sendiri. Ibunya tidak akan pulang selama berjam-jam.
"Itu tidak terlihat seperti hari pertama yang bagus."
Caitlin berbalik, terkejut pada suara Ibunya. Dia duduk di sana, di sofa, mengisap sebuah rokok, telah mengamati Caitlin dan mencibir.
"Apa yang kau lakukan, sudah merusak sweater itu?
Caitlin melihat ke bawah dan menyadari untuk pertama kalinya ada noda; mungkin akibat menabrak semen.
"Kenapa ibu ada di rumah lebih awal?" tanya Caitlin.
"Hari pertama bagiku, juga, tahu kan," tukasnya. "Kau bukan satu-satunya. Pekerjaan ringan. Bos menyuruhku pulang lebih awal."
Caitlin tidak tahan dengan nada nakal Ibunya. Tidak malam ini. Ia menghina kepadanya, dan malam ini, Caitlin merasa muak. Ia memutuskan untuk memberinya rasa obat-obatannya sendiri.
"Bagus," balas Caitlin. "Apa itu berarti kita pindah lagi?"
Ibunya tiba-tiba melompat berdiri. "Berhati-hatilah dengan ucapanmu itu!" teriaknya.
Caitlin tahu Ibunya sudah menunggu sebuah alasan untuk berteriak padanya. Ia pikir itu cara terbaik hanya untuk memancingnya dan segera menyelesaikannya.
"Kau seharusnya tidak merokok di depan Sam," jawab Caitlin dingin, lalu memasuki kamar tidur kecilnya dan membanting pintu di belakangnya, menguncinya.
Segera, Ibunya menggedor pintu.
"Kau keluar ke sini, anak sialan! Cara bicara semacam apa kepada ibumu!? Siapa yang menaruh roti di mejamu...."
Pada malam ini, Caitlin, perhatiannya sangat teralihkan, bisa meredam suara Ibunya. Sebaliknya, ia memutar ulang benaknya atas peristiwa hari itu. Suara-suara tawa remaja laki-laki itu. Suara detak jantungnya sendiri di telinganya. Suara raungannya sendiri.
Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ia mendapatkan kekuatan semacam itu? Apakah itu hanya dorongan adrenalin saja? Suatu bagian dari dirinya berharap demikian. Tapi bagian lain dari dirinya tahu itu bukan seperti itu. Apakah sebenarnya?
Gedoran di pintu berlanjut, tapi Caitlin hampir tidak mendengarnya. Ponselnya ada di mejanya, bergetar dengan gilanya, menyala-nyala dengan Pesan Instan, SMS, email, obrolan Facebook - tapi ia hampir tidak bisa mendengarnya juga.
Ia menggerakkan jendela kecilnya dan melihat ke bawah ke Amsterdam Ave, dan suara baru muncul dalam benakmya. Itu adalah bunyi suara Jonah. Gambaran senyumnya. Suara yang rendah, dalam dan menenangkan. Ia mengingat bagaimana lembutnya dia, bagaimana rapuhnya dia. Lalu ia melihatnya terbaring di tanah, berlumuran darah, alat musik berharganya hancur. Sebuah gelombang kemarahan baru muncul.
Kemarahannya berubah menjadi kekhawatiran - khawatir apakah dia baik-baik saja, apakah dia pergi, apakah dia berhasil pulang. Ia membayangkan dirinya memanggilnya. Caitlin. Caitlin.
“Caitlin?”
Sebuah suara baru dari luar pintunya. Suara seorang anak laki-laki.
Bingung, ia menyentaknya.
"Aku Sam. Biarkan aku masuk."
Ia menuju pintunya dan menyandarkan kepala di depannya.
"Mama pergi," kata suara di sisi lain. "Keluar untuk beli rokok. Ayolah, biarkan aku masuk."
Ia membuka pintu.
Sam berdiri di sana, menatap kembali, kekhawatiran terukir di wajahnya. Pada usia 15 tahun, dia terlihat lebih tua dari usianya. Ia tumbuh lebih awal, hampir enam kaki, tetapi dia tidak berisi, dan dia kikuk dan kurus. Dengan rambut hitam dan mata coklat, warnanya mirip dengan miliknya. Mereka benar-benar terlihat istimewa. Ia bisa melihat kekhawatiran di wajahnya. Dia menyayanginya lebih dari segalanya.
Ia membiarkannya masuk, dengan segera menutup pintu di belakangnya.
"Maaf," katanya. "Aku hanya tidak bisa menghadapinya malam ini."
"Apa yang terjadi dengan kalian berdua?"
"Seperti biasanya. Dia menungguku pada saat aku masuk."
"Aku rasa dia baru saja mengalami hari yang sulit," kata Sam, mencoba membuat kedamaian di antara mereka, seperti biasanya. "Kuharap mereka tidak memecatnya lagi.
"Siapa peduli? New York, Arizona, Texas… Siapa yang peduli apa selanjutnya? Kepindahan kita tidak akan pernah berakhir."
Sam mengerutkan kening saat dia duduk di kursi mejanya, dan ia segera merasa bersalah. Ia kadang-kadang memiliki lidah yang tajam, berbicara tanpa berpikir, dan ia berpikir dapat menariknya kembali.
"Bagaimana hari pertamamu?" tanyanya, mencoba mengubah topik pembicaraan.
Dia mengangkat bahu. "Oke, kayaknya." Dia mengunci kursi dengan kakinya.
Dia mendongak. "Kau?"
Ia mengangkat bahu. Pasti ada sesuatu dalam ekspresi wajahnya, karena Sam tidak berpaling. Dia tetap menatapnya.
"Apa yang terjadi?"
"Tidak ada," katanya membela diri, dan berpaling lalu berjalan ke arah jendela.
Ia bisa merasakan dia mengamatinya.
"Kau terlihat...berbeda."
Ia berhenti sejenak, bertanya-tanya apakah dia tahu, bertanya-tanya apakah tampang luarnya menunjukkan perubahan. Ia menelan ludah.
"Gimana?"
Diam.
"Aku tidak tahu," dia akhirnya menjawab.
Ia memandang ke luar jendela, mengamati tanpa tujuan ketika seorang pria di luar pojok bodega menjatuhkan kantung uang seorang pembeli.
"Aku benci tempat baru ini," katanya.
Ia berbalik dan menghadap dia.
"Aku juga begitu."
"Aku bahkan berpikiran tentang..." dia menundukkan kepalanya, "...pergi."
"Apa maksudmu?"
Dia mengangkat bahu.
Ia menatap Sam. Dia terlihat benar-benar depresi.
"Ke mana?" tanyanya.
"Mungkin...mencari Ayah."
"Bagaimana caranya? Kita tidak ada ide di mana dia."
"Aku bisa mencoba. Aku bisa menemukannya."
"Bagaimana caranya?"
"Aku tidak tahu.... Tapi aku bisa mencoba."
"Sam. Ia mungkin meninggal sepanjang pengetahuan kita."
"Jangan bilang begitu!" teriaknya, dan wajahnya berubah merah menyala.
"Maaf," katanya.
Ia kembali tenang.
"Tapi apakah kau pernah mempertimbangkan bahwa, bahkan jika kita menemukan dia, dia mungkin sama sekali tidak ingin menemuai kita? Selain itu, dia pergi. Dan dia tidak pernah mencoba menghubungi kita."
"Mungkin karena Ibu tidak mengizinkan dia melakukannya."
"Atau mungkin karena dia tidak menyukai kita."
Kerutan Sam semakin dalam ketika ia memainkan jari kaki ke lantai lagi. "Aku mencarinya di Facebook."
Mata Caitlin terbuka lebar karena terkejut.
"Kau menemukannya?"
"Aku tidak yakin. Ada 4 orang dengan namanya. 2 dari mereka adalah pribadi dan tidak ada foto. Aku mengirimi mereka berdua sebuah pesan."
"Dan?"
Sam menggelengkan kepalanya.
"Aku belum menerima balasannya."
"Ayah tidak akan mungkin ada di Facebook."
"Kau tidak tahu kan," jawabnya, sekali lagi membela diri.
Caitlin mendesah dan berjalan menuju ranjangnya dan berbaring. Ia memandang ke atas ke langit-langit kuning, cat yang mengelupas, dan bertanya-tanya bagaimana mereka semua telah mencapai titik ini. Ada kota-kota mereka merasa gembira di situ, bahkan saat-saat ketika Ibu mereka tampak hampir bahagia. Seperti ketika dia mengencani pria itu. Cukup bahagia, paling tidak, untuk meninggalkan Caitlin sendirian.
Ada kota-kota, seperti yang terakhir, di mana baik ia dan Sam membuat beberapa teman baik, di mana tampaknya seperti mereka mungkin benar-benar tinggal - setidaknya cukup lama untuk lulus di satu tempat. Dan kemudian itu semua nampaknya berubah dengan cepat. Berkemas lagi. Mengucapkan selamat tinggal. Apakah terlalu berlebihan meminta masa kanak-kanak yang normal?
Читать дальше